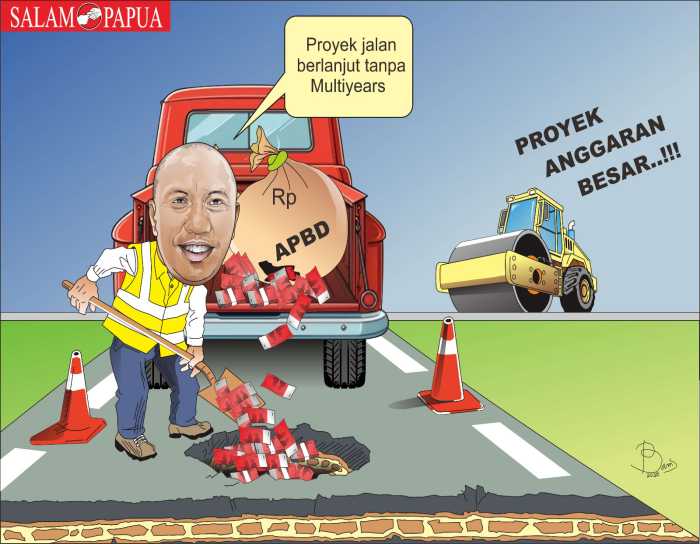SALAM PAPUA (TIMIKA)- SETIAP kali kita mendengar kabar
jatuhnya pesawat di Papua, duka mendalam kembali menyeruak. Bukan sekadar angka
korban jiwa, melainkan kenyataan pahit bahwa transportasi udara di tanah Papua
adalah nadi kehidupan.
Dari kota hingga pedalaman, dari Timika hingga Wamena,
pesawat kecil dan helikopter bukan sekadar moda transportasi, melainkan
jembatan yang menghubungkan harapan masyarakat di lembah-lembah terisolasi.
Namun, harus diakui, Papua memiliki tantangan alam yang
tidak dimiliki wilayah lain di Indonesia. Pegunungan Jayawijaya berdiri gagah
dengan jurang-jurang curam, lembah berkabut, dan awan pekat yang bisa muncul
dalam hitungan menit. Pilot yang terbang di atas Papua dituntut lebih dari
sekadar keahlian teknis mereka harus membaca tanda-tanda alam, mengenali jalur
sempit di antara bukit, dan berhadapan dengan cuaca yang sulit diprediksi.
Seringkali, faktor-faktor ini menjadi penyebab kecelakaan.
Pesawat yang sudah berumur, landasan pendek yang licin karena hujan, atau
sekadar kabut tebal yang menutup pandangan dalam sekejap, bisa mengubah
penerbangan rutin menjadi tragedi. Tetapi, menyalahkan alam semata tentu tidak
adil. Alam Papua memang keras, namun justru di situlah letak tantangannya. Yang
lebih penting adalah sejauh mana pemerintah dan maskapai serius menyiapkan
sistem transportasi udara yang aman dan layak.
Kecelakaan demi kecelakaan seharusnya menjadi alarm bagi
negara. Modernisasi navigasi, radar, serta perawatan armada harus
diprioritaskan. Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur darat seperti
Trans Papua, agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada pesawat. Kita
juga perlu memikirkan bagaimana menyiapkan generasi pilot lokal yang mengenal
karakter Papua, sehingga bisa membawa pesawat dengan kepekaan terhadap geografi
dan budaya setempat.
Pada akhirnya, terbang di atas Papua bukan hanya perjalanan
dari satu titik ke titik lain. Ia adalah pertempuran antara manusia dan
tantangan alam, antara harapan hidup dan risiko maut. Selama jalan raya belum
sepenuhnya membuka keterisolasian, pesawat akan tetap menjadi tulang punggung.
Namun, sudah seharusnya tulang punggung ini dijaga dengan
serius bukan hanya demi menghindari tragedi berikutnya, tetapi demi memastikan
bahwa setiap sayap yang terbang di langit Papua benar-benar membawa keselamatan
dan harapan.
Lebih jauh lagi, kecelakaan berulang juga menciptakan
ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem transportasi udara. Investor enggan
menanamkan modal di wilayah pedalaman, distribusi hasil bumi seperti kopi dan
sayur mayur terhambat, dan pembangunan ekonomi lokal tersendat. Papua akhirnya
tetap terjebak dalam lingkaran isolasi padahal kekayaan alamnya melimpah.
Karena itu, mengurangi risiko kecelakaan pesawat di Papua
bukan sekadar isu teknis penerbangan. Ini adalah agenda sosial-ekonomi. Setiap
investasi untuk memperbarui armada, memperkuat navigasi, atau membangun
alternatif jalur darat sejatinya adalah investasi untuk kesejahteraan rakyat.
Negara harus melihat persoalan ini bukan hanya sebagai kecelakaan transportasi,
tetapi sebagai penghalang pembangunan manusia Papua.
Selama pesawat masih menjadi nadi utama Papua, keselamatan
penerbangan adalah harga mati. Setiap kecelakaan yang terjadi bukan hanya
tragedi di udara, melainkan juga pukulan terhadap masa depan sosial-ekonomi di
tanah Papua.
Setiap kali kecelakaan pesawat terjadi di Papua, publik
ramai menyoroti faktor teknis: cuaca buruk, topografi sulit, atau pesawat tua.
Namun jarang sekali pembahasan diarahkan pada aspek paling mendasar: kebijakan
negara dalam menjamin keselamatan transportasi udara dan membangun alternatif
jalur darat di Papua.
Transportasi udara memang tak terhindarkan di Bumi
Cenderawasih. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan rutin
menyalurkan subsidi angkutan udara perintis untuk menjaga konektivitas
antar-daerah. Bandara-bandara kecil pun dibangun, mulai dari Nduga hingga Intan
Jaya. Pemerintah daerah juga berperan dalam menjaga koordinasi, terutama
terkait operasional maskapai perintis. Tetapi, semua ini kerap berhenti di
infrastruktur fisik. Persoalan kualitas armada, perawatan rutin, dan kesiapan
sumber daya manusia justru belum disentuh serius.
Lebih jauh lagi, pembangunan jalan Trans Papua yang
digadang-gadang sebagai solusi darat sering tersendat akibat faktor keamanan,
keterbatasan anggaran, dan minimnya dukungan infrastruktur pendukung.
Akibatnya, ketergantungan pada pesawat tetap tinggi. Ironisnya, pemerintah
pusat dan daerah tidak menempatkan isu keselamatan penerbangan di Papua sebagai
prioritas nasional. Kecelakaan baru dianggap darurat ketika sudah merenggut
korban.
Padahal dampaknya jelas: setiap kecelakaan udara di Papua
bukan hanya tragedi kemanusiaan, pokok melonjak, layanan kesehatan terganggu,
dan pembangunan sosial berhenti. Ini adalah lingkaran masalah yang hanya bisa
diputus dengan kebijakan terpadu.
Negara tidak boleh melihat kecelakaan pesawat di Papua
sebagai “nasib buruk di wilayah sulit”. Pemerintah pusat harus memastikan
modernisasi navigasi, radar, dan armada pesawat di Papua sama seriusnya dengan
pembangunan MRT di Jakarta atau jalan tol di Jawa. Pemerintah daerah pun mesti
aktif, bukan sekadar menunggu bantuan pusat, tetapi berani mendorong kerja sama
strategis dengan maskapai, menyiapkan pilot lokal, hingga memastikan dana Otsus
benar-benar menyentuh sektor transportasi vital.
Jika Papua terus diperlakukan dengan paradigma darurat, maka
tragedi udara akan berulang. Tetapi bila negara berani menempatkan keselamatan
penerbangan dan pembangunan konektivitas sebagai hak dasar masyarakat Papua,
maka setiap sayap yang terbang di langit Papua bukan lagi sekadar taruhan,
melainkan benar-benar jembatan menuju masa depan yang lebih sejahtera.
Penulis: Sianturi